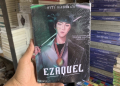KOTOMONO.CO – Sebagai generasi pencinta K-pop, rasanya ngulik hal-hal yang berbau-bau kekunoan tuh nggak banget deh. Tapi apa boleh buat, dosenku yang satu ini kasih tugas gitu. Ngulik soal asal-usul desa tempat tinggalku. So, timbang nggak dapat nilai di akhir semester, terpaksa kulakoni tugas itu. Dan perburuan pun dimulai.
Awalnya, aku nanya-nanya sama Ibu dan Bapak. Siapa kira-kira yang bisa aku mintai keterangan tentang cerita asal-usul desaku, Bumirejo. Eh, rupanya Ibu dan Bapak punya pandangan yang berbeda. Ibu merekomendasikan satu nama, sementara Bapak menyuruhku menemui nama lainnya. Hm… cukup bingung juga sih, siapa yang mesti aku temui. Tapi, daripada bingung akhirnya kuputusin aja untuk menemui dua-duanya.
Sesi wawancara pun dimulai. Satu per satu nama-nama itu kutemui. Mereka kaget sekaligus senang juga saat kuwawancarai. Panjang mereka bercerita. Kurekam semua pembicaraan. Kucatat poin-poin pentingnya. Lalu, setelah semua selesai, barulah kujadikan tulisan singkat ini. Ya, semacam laporan buat memenuhi tugas kuliah.
Rupa-rupanya, asal-usul nama Bumirejo itu punya kisah panjang. Nggak cuma panjang, tapi juga ada versi yang berlainan juga. Sebelum bernama Bumirejo, desa yang terletak di kawasan Kecamatan Pekalongan Barat ini dulunya bernama Kanyaran. Kata “Kanyaran” sendiri oleh sebagian besar warga desa Bumirejo (atau yang sekarang berubah jadi Pringrejo gara-gara dilebur bersama kelurahan Pringlangu) diambil dari kata “anyar”. Dalam bahasa Indonesia, kata “anyar” diartikan baru. So, boleh dibilang waktu itu desa Kanyaran adalah desa yang baru.
Baca juga : Penggabungan Kelurahan Tak Mungkin Mengusik Sejarah Lho
Meski begitu, ada juga yang menghubungkan kata “Kanyaran” itu dengan kata “nyara” (sengsara/susah). Kok begitu? Soalnya, kata “Kanyaran” itu semacam pengucapan yang dipendekkan dari kata “Kanyaraan”. By the way, mana yang tepat, aku nggak tahu. Yang jelas, dua informasi awal ini bagiku sangat penting. Aku nggak perlu mempersoalkan perbedaan itu. Kan katanya, perbedaan itu rahmat. Ya kan?
Lanjut! Kisah pun mengalir kemudian. Konon, jauh sebelum desa Bumirejo itu ada, kawasan ini awalnya hanya sebidang tanah kosong, rawa-rawa. Jangankan rumah, warga manusia pun nggak ada. Karena kawasan ini adalah rawa-rawa, maka dikenallah sebagai Rowoyoso. Terus, gimana ceritanya kok bisa jadi kawasan pedesaan yang berpenghuni ya?
Ceritanya gini nih. Pada masa pemerintahan Kolonial Belanda, penguasa berambut pirang, hidung mancung dan warna kulit pucat itu tengah sibuk memperluas jaringan perdagangan. Salah satu upaya mereka adalah dengan membangun jalan yang menghubungkan setiap kawasan. Entah kebetulan atau memang sudah direncanakan, Rowoyoso dipilih sebagai salah satu kawasan yang bakal dijadikan jalur lalu lintas perdagangan dan diplomatik.
Karena kondisi tanahnya berawa, maka tidak ada cara lain selain mengubah Rowoyoso menjadi lahan tanah yang padat. Tetapi, untuk bisa merealisasikan tujuan itu, rupanya mereka tak punya cukup tenaga dan modal. So, supaya keuangan dan tenaga mereka bisa dihemat, dibikinlah semacam sayembara. Mungkin kalau di era kekinian semacam lelang proyek gitu.
Isi sayembara itu, bagi siapa saja yang sanggup membangun jalan di Rowoyoso yang menghubungkan kawasan pesisir dan kawasan atas, ia akan diangkat jadi Bupati. Segera, informasi soal sayembara itu menyebar luas. Tetapi, tidak serta merta mendapatkan respon. Orang-orang cuma bisa saling memandang sambil menertawai isi sayembara itu. Apalagi mereka tahu, kalau Rowoyoso adalah tanah rawa-rawa. Butuh berapa banyak tanah untuk mengurugnya? Wah, jari-jari tangan saja nggak cukup untuk menghitungnya.
Di tengah-tengah pergunjingan dan diskusi yang nggak ada habisnya itu, kabar soal sayembara itu mampir ke telinga tokoh sesepuh desa. Namanya Kiai Klidin. Mula-mula, ia tak begitu saja percaya atas kabar itu. Maka, ia pun melakukan 5 M. Mencari kebenaran informasinya. Mengamati perkembangan informasi. Menyelidiki maksud dan tujuan. Menimbang baik-buruknya. Serta, mengatur strategi.
Ya dong! Mesti begitu. Soalnya, di balik upaya pemerintah Kolonial Belanda membuat proyek jalan itu pastinya ada maksud-maksud tertentu. Maksud yang cuma akan menguntungkan pemerintahan Kolonial Belanda. Jangan-jangan langkah itu sekadar tipu daya, semacam strategi mereka untuk membuat masyarakat takluk dan tunduk. Jangan-jangan langkah itu hanya untuk mencari orang yang bisa dijadikan alat kekuasaan mereka.
Atas pertimbangan itu, Kiai Klidin beserta putranya Warijah, akhirnya mengambil kesempatan itu. Tentu, ini dilakukan dengan sangat hati-hati dan rapi. Sangat diperhitungkan pula soal kemungkinan-kemungkinan buruknya. Keduanya sepakat, bahwa langkah mereka itu dilakukan agar proyek itu tidak jatuh ke tangan orang yang salah, orang yang kelak akan menjadi kacungnya Belanda. Sebab, jika itu terjadi, maka nasib warga akan jauh lebih sengsara dengan membebani upeti yang besar sebagai imbalan dan usaha mengeruk keuntungan dari proyek itu.
Kiai Klidin dan Warijah pun segera menemui pimpinan Belanda. Menyatakan kesanggupannya untuk membangunkan jalan. Tapi, kira-kira waktu itu ada penandatanganan MoU nggak ya? Atau semacam teken kontraklah.
Singkat cerita, Kiai Klidin dan Warijah pun mulai mengumpulkan orang-orang untuk menjadi pekerja proyek. Ya, ini kesempatan emas untuk membuka lapangan kerja bagi warga. Sekaligus sebagai cara Kiai Klidin dan Warijah untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Mereka yang turut membangun jalan itu merasa dilibatkan dalam proses awal pembangunan sebuah kawasan hunian. Mereka itulah yang kelak akan mempertahankan setiap senti tanah kelahiran mereka.
Segala daya dikerahkan. Rawa dijadikannya tanah padat. Beberapa rumah didirikan. Pemukiman-pemukiman kecil pun turut dibangun. Dibangun pula sungai untuk mengalirkan air rawa-rawa. Sebagai seorang ahli ilmu bumi, Warijah lantas membangun sungai itu dengan mengalirkan sungai melintasi beberapa desa di dekat Rowoyoso. Ini dilakukan, agar sungai itu dapat digunakan pula untuk pengairan sawah-sawah di seluruh desa yang dilintasi sungai. Lantas, sebagai ujung dari sungai itu ditembuskan ke sungai Sambo (Kali Meduri). Teknik semacam ini, pada masa itu difungsikan pula untuk menanggulangi luapan air di kala musim hujan tiba, juga untuk menanggulangi dampak air pasang.
Tetapi, oleh sebagian warga Bumirejo, kelokan sungai yang dibangun Warijah ini diartikan sebagai sesuatu yang membingungkan. Maka, berkembang pula cerita kalau saat Warijah hampir menyelesaikan sungai mengalami kebimbangan. Ia merasa bimbang, apakah sungai harus lurus atau belok. Tetapi pada akhirnya, diputuskan untuk membelokkan aliran sungai.
Kalau diamati, sampai saat ini arus sungai di Desa bumirejo akan berputar terlebih dahulu saat berada di belokan aliran yang dulunya menjadi ujung dari Rowoyoso. Setelah itu, arus air akan kembali diteruskan hingga ke sungai Sambo. Warga beranggapan bahwa air tersebut mengalami kebingungan, warga biasa menyebutnya “banyune bingung” (airnya bingung). Oleh sebab itu terdapat sebuah jembatan di desa Bumirejo yang diberi nama “Brok sebingung” oleh warga setempat.
Kembali ke cerita Mbah Warijah. Selesai mengerjakan proyek itu, Warijah menagih janji sesuai kesepakatan awal. Namun janji tinggallah janji, seperti kulit pisang yang tercampakkan setelah buahnya dimakan, kesepakatan tak bisa lagi ditegakkan. Warijah hanya diupah dengan jabatan lurah di pemukian Rowoyoso. Mungkin karena penguasa Belanda tahu jika maksud Warijah adalah sebuah upaya diam-diam untuk melawan kekuasaan Belanda. Mungkin juga karena Belanda tahu jika Warijah dan Kiai Klidin adalah sosok yang berpengaruh. Belanda khawatir, jika keduanya melawan maka akan terjadi gelombang perlawanan yang besar dari masyarakat, lebih-lebih ketika Warijah diberi kedudukan sebagai Bupati.
Tak terima dengan perlakuan Belanda, Warijah ngelabrak kantor pemerintahan Koloial Belanda yang ada di Pekalongan. Saat itu, para penggedhe Belanda merasa mendapat angin segar. Itulah waktu yang memang ditunggu-tunggu. Kesempatan emas datang. Segera mereka melakukan muslihat untuk meringkus Warijah yang cerdasnya nggak ketulungan itu.
Sebuah peti disiapkan bagi jasad Warijah. Para penggedhe pemerintah Kolonial Belanda lantas pura-puralah membikin perundingan di dalam ruang kantor. Tetapi, di saat itu Warijah disekap. Tubuh Warijah lantas dimasukkan peti. Tak ada lubang secuil pun. Selepas itu, peti dilepaskan ke laut dan hanyut.
Berhari-hari peti itu terombang-ambing di lautan. Sampai pada akhirnya sampai di sebuah pulau. Ada yang bilang, pulau yang dimaksud adalah Karimun Jawa, Jepara. Sampai di tepian pulau, sejumlah warga yang melihat peti itu membawanya ke darat. Lalu, ketika dibuka peti itu mereka terkejut. Yang ada di dalam peti itu adalah seorang manusia, yaitu Warijah. Herannya lagi, orang yang ada di dalam peti itu masih hidup dan sehat. Mereka segera mengangkat dan memapah tubuh Warijah.
Berjalannya waktu, bergantinya angka tahun, warga pulau itu pun mengenal Warijah semakin dekat. Mereka akhirnya tahu, jika Warijah bukanlah orang biasa. Maka, mereka pun mendudukkan Warijah sebagai tokoh sesepuh di desa itu. Di sana pula, Warijah menetap hingga akhir hayatnya.
Konon, seorang pelayar asal Pekalongan yang sempat singgah di pulau Karimun Jawa pernah menemukan keberadaan makam yang pada nisannya bertuliskan nama Mbah Warijah Pekalongan. Bahkan, ada juga nama desa di sana yang namanya sama persis dengan nama kota ini, Pekalongan. Tepatnya di kecamatan Batealit Kabupaten Jepara. Kepastian benar tidaknya soal itu belum dapat dijelaskan secara pasti. Namun, warga Bumirejo meyakini cerita tersebut.
Nah, balik lagi ke Rowoyoso. Setelah kejadian itu, Rowoyoso mulai didatangi warga dan bermukim di sana. Semakin ramai dan padat. Sampai akhirnya menjadilah sebuah desa, Desa Rowoyoso. Lantas, seiring makin banyaknya warga baru yang mukim di desa itu, nama desa itu diubah menjadi “Kanyaran”. Yang artinya baru. Karena desa tersebut masih baru, kehidupan warga juga belum stabil. Tak heran jika kemudian warga desa Kanyaran itu mentahbiskan makna lain pada kata “Kanyaran” sebagai kondisi yang serba susah.
Selang beberapa waktu, adanya peralihan kota dan kabupaten sehingga desa Kanyaran masuk ke dalam pemerintahan Kota. Kemudian berubah nama menjadi desa Bumirejo. Bumirejo dari kata “Bumi” yang artinya bumi atau bermaksud sebuah desa. “Rejo” dalam KBBI memiliki arti welas asih, penyayang dan dami, namun warga beranggapan kata “rejo” merupakan singkatan dari “Rejekine Bejo”. Nama tersebut mejadi sebuah harapan bagi desa tersebut untuk menjadi bumi atau desa yang damai, jaya bagi warga dan desa Bumirejo itu sendiri.
Baca juga : Sejarah Asal-usul Kelurahan Bumirejo Kota Pekalongan
Saat ini desa Bumirejo sudah menjadi desa yang ramai dan telah banyak perubahan, namun cerita sejarah ini masih berdampingan dan melekat di kehidupan masyarakat hingga kini, terbukti dengan masih terjaganya makam milik Kyai Klidin di Bumirejo.
Ah! Rasanya nggak sia-sia juga sebenarnya aku mendapatkan tugas ini. Minimal biar aku melek tentang tanah kelahiranku sendiri. Ya, kisah asal-usul bagaimana pun itu penting untuk dicatat dan diingat. Supaya kita tahu, untuk apa kita dihadirkan di dunia ini.