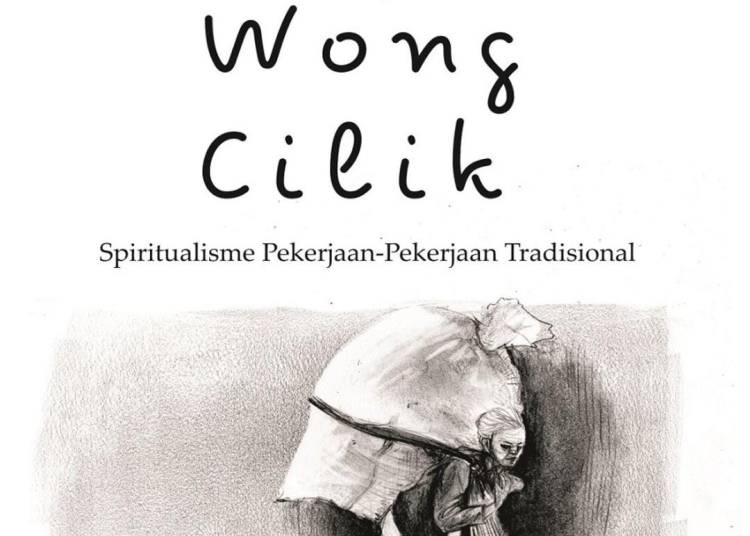KOTOMONO.CO – Sebuah resensi buku Profesi Wong Cilik karya Iman Budhi Santosa
Saya teringat salah satu esai Kuntowijoyo berjudul Musyarakah dan Jama’ah dalam Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia (2017). Dalam esai tersebut Pak Kunto menyinggung perihal hilangnya kerja sambatan yang ada di desa. Dulu ketika orang desa akan mendirikan rumah, warga sekitar akan berbondong-bondong secara suka-rela menyumbangkan apa yang bisa dikerjakan (sambatan).
Hari ini, kerja-kerja sambatan seakan-akan sudah luntur. Semua serba transaksional. Orang akan bekerja jika dibayar dan hanya itulah tujuan bekerja. Aspek-aspek spiritual pada pekerjaan modern seakan hilang entah ke mana dan digantikan aspek material: uang.
Sekarang udah jarang kita temui mereka yang bekerja untuk pekerjaan itu sendiri. Di zaman yang serba modern ini, semuanya sudah terkalkulasi dengan baik di dalam genggaman: gawai. Semisal akan berbelanja, dulu kita harus pergi ke pasar dan menemukan harga yang cocok antara penjual dan pembeli. Ada interaksi dan emosional yang terjalin di sana.
Hari ini, semua urusan jual beli sudah selesai dengan satu jari: dengan menggulir marketplace. Bukan hanya itu, semua profesi hari ini hampir serba digital di bawah bendera era 4.0, lebih-lebih akan digantikan dengan kecerdasan buatan 5.0.
Wong Cilik: Mati-Matian Menyambung Hidup
Pernahkah kalian mendengar profesi penangkap perkutut? Atau pemanjat kelapa? Atau mungkin penggali sumur? Ya, setidaknya itu adalah di antara kegiatan yang di-profesi-kan oleh masyarakat Jawa dahulu. Di zaman kiwari, hampir-hampir sudah tidak ditemukan lagi pekerjaan-pekerjaan tradisional tersebut, bahkan tidak percaya bahwa itu merupakan suatu profesi. Buku yang ditulis Iman Budhi Santosa ini mengantarkan kita untuk melakukan refleksi pada dunia kerja pada masyarakat tradisional Jawa.
Berbekal interaksi langsung dengan para pekerja tradisional, Romo Iman berhasil memotret sisi-sisi kehidupan dari wong cilik berdasarkan profesinya. Pekerjaan-pekerjaan yang disebutkan dalam buku ini adalah pekerjaan yang memang hanya bisa dilakukan oleh wong cilik.
Agaknya sangat susah membayangkan jika seorang priayi menjadi tukang gali sumur, seorang bangsawan menjadi pemetik teh atau seorang yang berpangkat memilih menjadi jagal sapi, kecuali memang mereka memilih jalan yang terjal ini.
Wong cilik adalah mereka yang berada dalam kasta paling bawah dari stratifikasi sosial masyarakat Jawa. Mereka biasanya tinggal di desa, di kawasan yang jauh dari pusat-pusat kegiatan masyarakat. Meminjam bahasa Kuntowijoyo (2003), wong cilik adalah mereka yang terpinggirkan dari perkembangan kota dan hanya sebagai penonton dalam perayaan-perayaan yang diadakan oleh priayi.
Maka sudah hal yang biasa apabila wong cilik seringkali lebih memilih duduk di paling belakang dalam sebuah acara. Dalam buku Suta Naya Dhadhap Waru (2017), Romo Iman menggambarkan bahwa kehidupan wong cilik itu layaknya tumbuhan. Kedudukan tumbuhan hanya ditentukan berdasarkan fungsinya bagi manusia.
Begitu juga wong cilik yang kedudukannya ditentukan oleh seorang yang memiliki pangkat, semat dan drajat, dengan kata lain adalah mereka yang punya kuasa.
Hanya berbekal keterampilan, keuletan dan konsistensi, wong cilik mati-matian untuk menyambung hidup. Mati-matian di sini mengindikasikan adanya usaha yang berlebih untuk sekadar pemenuhan kebutuhan hidup, yang kadangkala tidak sempat memikirkan dana untuk tabungan.
Pekerjaan wong cilik adalah pekerjaan kasar. Rekasane sepiro, kayane ra sepiro (Usahanya seberapa, hartanya tak seberapa). Seperti pekerjaan-pekerjaan yang menjadikan nyawa sebagai taruhannya: pemanjat kelapa, penggali sumur dan kuli panggul.
Pemanjat kelapa adalah profesi yang membutuhkan nyali yang tinggi untuk menapaki pohon kelapa. Sedikit saja terjadi kesalahan dalam memanjat, jika tidak berakhir di rumah sakit berarti pemakaman. Begitu juga dengan penggali sumur. Ia dituntut untuk menggali tanah sampai menemukan sumber air di kedalaman sekian meter sampai menemukan air.
Namun penghasilan yang didapat dari kerja-kerja tersebut tidaklah seberapa. Bagi orang Jawa yang masih menjunjung tinggi rasa tepa slira, mungkin akan mudah mengatakannya dengan sumangga kersa: berapa pun akan ia terima.
Hal itu sebagaimana dipotret oleh Romo Iman melalui tukang becak di Yogyakarta pada dekade 90-an. Atau mungkin seorang pemandu gunung yang pantang menerima/mematok imbalan atas jasanya mengantar pendaki. Sebagaimana Mbok Jaga, seorang pemandu Gunung Merbabu yang mengantarkan Romo Iman sampai di puncak pada tahun 1976.
Nilai Hidup Wong Cilik dalam Keprofesiannya
Begitulah Wong cilik, betapapun profesinya tidak menjadikan kaya harta, tetapi laku-lakunya kaya akan nilai-nilai spiritualitas. Banyak nilai-nilai yang bisa dipetik dari lelaku kerja wong cilik. Seperti bagaimana seorang kuli panggul tidak pernah memiliki persaingan antar sesamanya.
Konsep “rezeki tidak akan ke mana” rupanya masih mengakar pada jiwa-jiwa wong cilik. Pasalnya dirinya tahu, bahwa Yang Kuasa tidak akan salah memberi rezeki. Jika tidak rezekinya, berarti bukan haknya. Sederhana.
Meskipun pekerjaan-pekerjaan tradisional tersebut sudah hilang, bukan berarti kita meninggalkan semua secara keseluruhan. Ada banyak kebijaksanaan yang bisa kita ambil dalam sikap hidup keprofesian wong cilik. Ada semangat untuk tidak terlalu mengejar duniawi, kedonyan. Ada pula laku etos kerja yang tinggi dengan tetap narimo ing pandum.
Barangkali, sejauh kita masih memegang nilai-nilai luhur para pekerja tradisional, kita bisa mencairkan sekat-sekat transaksional antar individu dalam semangat solidaritas, kolektif, atau kerja-kerja sambatan.