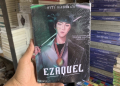Kotomono.co – Produktivitas dari Didi Kempot dalam menggubah lagu layak diacungi jempol. Melalui tangan dinginnya, ratusan lagu telah berhasil dilahirkan. Dari ratusan lagu itu, Didi Kempot begitu kondhang akan lagu-lagu bertema asmara, terutama patah hati.
Melaluinya, Didi Kempot mengajak pendengar untuk merayakan kesedihan daripada meratapinya. Hal itu lantas mengantarkan Didi sebagai “Bapak Patah Hati”. Sebenarnya, Didi Kempot tidak hanya menggubah lagu bertema asmara saja. Ada juga banyak lagu bertema lain yang telah digubahnya. Hanya saja, lagu-lagu itu kalah populer dengan lagu bertema patah hati. Dari jejak yang ada, Didi pernah menggubah lagu yang berisi tentang kritik-kritik sosial.
Kritik
Sejauh ini, musik seringkali hanya dipahami sebagai katarsis estetis yang cukup dinikmati bunyinya. Lebih dari itu, musik juga digunakan sebagai katalisator untuk meluapkan kepentingan sang penggubah. Entah itu kepentingan agama, sosial, politik, dan sebagainya. Begitu pula dengan Didi Kempot yang menggunakan musik sebagai katalisator untuk mengkritik.
Didi Kempot pernah menggubah lagu bertajuk “Alas Gundul” (2007) yang mengisahkan tentang pembabatan hutan. Syairnya menceritakan tentang bocah penggembala yang sulit mencari makan, kambing yang sulit mencari dedaunan, pohon-pohon hilang hanya tinggal akarnya. Imbasnya, banjir bandang menerka. Melalui lagu “Alas Gundul”, Didi Kempot ingin memantik kesadaran manusia agar menjaga hutan. Hutan adalah kehidupan. Tanpanya, keberadaan makhluk hidup mungkin akan sirna.
BACA JUGA: Sapu Lidi – Dari Falsafah, Penolak Bala, Penolak Hujan, Hingga Cerita Rakyatnya
Tidak hanya “Alas Gundul”, Didi Kempot bermanuver lagi dengan mengeluarkan lagu bertajuk “Gunung Dieng” (2007). Lagu ini mengisahkan tentang pembabatan pohon dan penggerusan tanah yang berlebihan di Gunung Dieng. Didi Kempot ingin mengingatkan agar tidak berlebihan dalam mengeksploitasi Gunung Dieng. Masih ada anak-cucu yang perlu dipikirkan ke depannya.
Bukan hanya ikhwal hutan, Didi Kempot juga meluapkan keresahannya dalam hal air dan pertanian. Lihat saja karya bertajuk “Bapak Gubernur” (2007). Dalam karya itu, Didi Kempot mengeluhkan nasib seorang petani yang kurang makmur. Tanaman petani banyak yang hancur. Imbasnya, harga tanaman itu akan turun. Penyebabnya ialah air irigasi yang tercemari oleh limbah. Melalui lagu itu, Didi meminta Bapak Gubernur untuk menyelesaikan pencemaran tersebut.
Keresahan tentang air juga termuat dalam lagu bertajuk “Kemampul” (2007) dan “Salahe Sopo” (2007). Dalam ke dua lagu itu, Didi Kempot mengeluhkan tentang air sungai yang tidak lagi bersih. Padahal, sewaktu kecil ia sering mandi di sungai. Sungai yang sejatinya mampu menghidupi, kiwari berubah menjadi sumber penyakit. Didi Kempot ingin mengingatkan bahwa air adalah kehidupan. Bukanlah salah dari air jika ia bisa menghadirkan penyakit. Sebab, itu adalah pantulan dari sikap manusia yang tidak menjaga air.
BACA JUGA: Makna dan Tuntunan Perilaku Hidup di Balik Pintu Gebyok
Tidak hanya air dan hutan, Didi Kempot juga menyuarakan kritikannya tentang udara. Kritikan itu ia luapkan melalui lagu bertajuk “Kotekan Lesung” (2007). Didi Kempot meluapkan keresahan mengenai mesin-mesin yang telah menggeser keberadaan manusia. Kultur pertanian yang sebelumnya dekat dengan gotong-royong dan kerukunan akhirnya kalah dengan mesin yang cenderung dikerjakan oleh individu. Di sisi lainnya, mesin mengeluarkan asap yang mencemari udara pedesaan. Udara yang sebelumnya segar, berubah menjadi pengap menyesakkan.
Wong Cilik
Rasanya, terlalu sempit apabila membicarakan karya Didi Kempot hanya dalam batasan tema patah hati. Realitanya, Didi Kempot telah membekukan karya-karya bertema kritik sosial. Melaluinya, ia melayangkan asa agar semua pihak menyadari pentingnya alam bagi kehidupan manusia.
Didi Kempot dalam menyajikan karya-karya tersebut terasa sangat otentik. Pertama, musikalitas yang digunakan ialah campursari. Musik itu identik dengan musiknya wong cilik. Ia kerap dikumandangkan dalam kereta kelinci, radio pedesaan, terminal, dan lain sebagainya. Ke dua, cara ia memilih dan menata syairnya benar-benar mewakili wong cilik. Mandi di sungai, penggembala kambing, gotong-royong, ataupun lesung—alat penumbuk padi. Ada persenyawaan antara syair dan musik yang disajikan oleh Didi Kempot. Rasanya, karya itu sangat jujur. Didi Kempot benar-benar mewakili kaum wong cilik.
BACA JUGA: Angka dan Manusia Jawa, Laku Kehidupan, Kearifan, dan Semesta
Selama ini, wong cilik—akar rumput selalu pasrah akan keadaan yang dideranya. Mereka menerima apapun sebagai lakon hidupnya. Air irigasi yang tercemar oleh limbah pabrik, pohon yang dibabat habis oleh penguasa, ataupun hilangnya persawahan ialah peristiwa pilu yang diterimanya dengan lapang. Mereka takut untuk berbicara kepada kaum priyayi ataupun bangsawan. Mereka menyadari bahwa wong cilik mempunyai kodrat seperti itu.
Didi Kempot dan lagunya laksa oase yang menyegarkan. Ia menjadi juru bicara bagi wong cilik untuk melayangkan asa mereka di tengah ketakutan yang dialaminya. Entah terdengar ataupun tidak, hal terpenting adalah mengikhtiarkannya. Campursari dan wong cilik adalah perpaduan yang ciamik. Dalam hal ini, Didi Kempot berhasil meleburkannya.