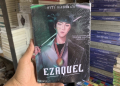KOTOMONO.CO – Imbauan Bawaslu agar tidak melakukan politisasi masjid mendapat respons beragam, namun intinya pro dan kontra. Mereka yang pro berpendapat bila masjid adalah tempat ibadah yang harus disterilkan dari segala kegiatan politik praktis karena itu dapat merusak kesucian masjid.
Sebaliknya, mereka yang kontra berpendapat bahwa standar politisasi masjid seringkali ditentukan secara subjektif, sehingga imbauan tersebut sangat kental dengan Islamophobia. Lagi pun, kata mereka, masjid tak saja tempat ibadah namun juga pusat peradaban umat Islam. Karenanya, pembicaraan soal politik tak sepatutnya tabu dalam masjid.
Imbuan tidak mempolitisasi masjid
Imbauan agar tak mempolitisasi masjid bukan tanpa duduk persoalan. Setidaknya sejak Pilgub DKI Jakarta 2017, masjid kerap kali digunakan untuk membangun solidaritas politik yang kemudian dituduh lawan politik sebagai gerakan politik identitas, intoleransi, dan antikebinekaan. Karenanya, masjid juga kerap dituduh sebagai corong ujaran kebencian, alih-alih sebagai oase kesejukan.
Memang, tak satu pun yang meragukan kesahihan kisah multifungsinya masjid di era Nabi Muhammad. Namun, yang menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana seharusnya masjid berfungsi sebagai sarana muamalah/interaksi sosial umat Islam?
Sungguh pun isu politisasi masjid telah memicu polemik luar biasa, di sisi lain saya merasakan ada gejala positif pada banyak masjid di Indonesia akhir-akhir ini. Banyak masjid yang telah muncul kesadaran bahwa masjid harus bisa memberikan manfaat lebih bagi para jamaahnya. Muncul kesadaran pula bahwa membangun masjid tak lagi bisa ditafsirkan hanya sebatas membangun menara, memasang AC, membeli karpet rol mahal, dan lain-lain, meski memang itu semua dapat menunjang kegiatan peribadatan masjid.
Masjid bermanfaat
Banyak masjid hari ini yang berkompetisi membangun sekolah, minimart, klinik pengobatan, dan lain sebagainya. Di samping juga berlomba memperkokoh bangunan masjid menjadi lebih megah dan mewah. Sebagai contoh, Masjid Jogokariyan Yogyakarta terkenal dengan saldo kasnya yang selalu nol rupiah karena dana infak jamaahnya sukses memberdayakan jamaah dan warga sekitarnya.
Banyak masjid juga yang kemudian disulap menjadi nyaman, senyaman kafe tongkrongan favorit anak-anak muda, sebagaimana Masjid Muslim United di Ring Road Utara Yogyakarta. Masjid Muslim United memiliki branding program kerja yang sangat menarik anak-anak muda untuk datang ke masjid tersebut. Setidaknya itulah yang saya lihat di akun Instagram resminya.
BACA JUGA: Sekelumit Tentang Potret Dinasti Politik di Indonesia
Seorang budayawan yang juga guru besar antropologi UGM, mendiang Prof. Kuntowijoyo, pernah mengkritik masjid dalam salah satu bukunya, Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia (1985). Masjid disebutnya tak ada bedanya dengan halte bus, di mana masjid hanya didatangi seperlunya dan ditinggal setelah selesai.
Menurutnya, masjid seringkali hanya dipandang sebagai tempat ngaso sejenak dari rutinitas harian. Tak heran bila selepas salat berjamaah, banyak jamaah yang kalau tidak langsung bablas pulang, ya tiduran di teras masjid. Adapun yang sempat jagongan, pasti itu sesama yang saling kenal, bukan dua orang yang sama-sama baru berjumpa di masjid lalu mencoba saling akrab.
Masjid dan peradaban Islam
Supaya masjid betul-betul berfungsi sebagai pusat peradaban umat Islam, Kuntowijoyo menyarankan agar solidaritas umat harus dibangun dari masjid. Nah, di sinilah persoalan utamanya. Solidaritas umat Islam selama ini masih belum menyentuh titik pusat kehidupan mereka, yaitu sosial-ekonominya. Solidaritas umat Islam masih baru sampai pada solidaritas politik.
Ada dua sisi gelap pembangunan solidaritas politik umat Islam di masjid. Selain rentan dituding macam-macam oleh lawan politik, solidaritas macam itu disebut Kuntowijoyo sangat rapuh. Solidaritas politik umat Islam seringkali dipupuk di masjid kalau dekat-dekat Pemilu, sehingga Pemilu selesai solidaritasnya pun ikut selesai. Umat Islam kembali jadi buih di lautan, jumlahnya banyak tapi mudah terombang-ambing entah ke mana.
BACA JUGA: Strategi Politik Dibalik Gelar Tituler Untuk Deddy Corbuzier
Ditambah lagi, banyak khatib atau penceramah yang menarasikan bila umat Islam hari-hari ini termarjinalisasi dari segala aspek kehidupan. Saya tak menafikan bahwa marjinalisasi umat Islam dari segala aspek memang nyata adanya. Namun, langsung gebyah uyah mengatakan bahwa politik adalah satu-satunya jalan untuk meretas marjinalisasi itu adalah opini yang sempit sekali. Kok bisa?
Kuntowijoyo juga mengingatkan dalam buku yang sama, bahwa tidak segala hal dapat tuntas dengan politik, meski bukan berarti umat Islam lebih baik buta politik. Dalam bahasa Kuntowijoyo, umat Islam memang harus melek struktur, namun pembicaraan seputar politik tidak harus di masjid.
Kuntowijoyo di lain buku, Muslim Tanpa Masjid (2002), mengatakan bila keilmuan umat Islam terdiri dari tiga fase. Fase pertama adalah umat memandang Islam sebagai mitos, di mana ada anggapan bila semua problem selesai dengan Islam. Fase kedua adalah ideologisasi Islam, di mana Islam dipakai sebagai alat perjuangan. Fase ketiga adalah Islam sebagai ilmu atau ide yang lebih kongkret.
BACA JUGA: Nuansa Masjid Raya Sheikh Zayed Solo Ala Vibes Abu Dhabi
Nah, fenomena politisasi masjid adalah irisan fase pertama dan kedua. Kedua fase itu barangkali relevan bila dalam situasi penjajahan kolonial dulu, tetapi jelas tidak relevan dalam konteks sudah merdeka seperti sekarang. Tak heran bila politisasi masjid seringkali dituduh sektarian dan intoleran.
Selain itu, semestinya, sekian banyak umat Islam itu memiliki beragam profesi dan keahlian. Ada yang ahli merumuskan hukum Islam, ahli dalam ekonomi, ahli kemasyarakatan, ahli kesehatan, dan lain-lain. Persatuan umat Islam jangan dimaknai sebagai umat Islam berjumlah banyak masuk satu sektor tertentu, apalagi kalau hanya masuk ke politik.
Apa yang dilakukan Masjid Jogokariyan dan Masjid Muslim United tadi merupakan contoh bagaimana solidaritas sosial-ekonomi dapat dibangun. Kuntowijoyo mengatakan, solidaritas sosial bisa menjauhkan umat Islam dari perpecahan sosial, sementara solidaritas ekonomi akan membuat kemiskinan dan kesenjangan umat Islam dapat digerus perlahan.
Intinya, kegagapan para takmir masjid dalam merancang dan mengeksekusi program kerja yang kreatif, inovatif, dan progresif adalah sumber masalahnya. Memakmurkan masjid adalah kerja jangka menengah hingga panjang, sehingga hasilnya harus berkelanjutan dari generasi ke generasi.
BACA JUGA: Nuansa Majapahit Modern nan Islami ala Masjid Raden Patah Universitas Brawijaya
Solidaritas politik sulit menjawab tantangan tersebut, sebab dalam politik tak ada yang abadi selain kepentingan dan arah angin mudah sekali berubah karenanya. Sebaliknya, solidaritas sosial-ekonomi mampu menjawabnya karena benefitnya lebih terasa kongkret bagi masyarakat dan bisa terhitung berpartisipasi dalam pembangunan nasional dari level akar rumput juga, lho.
Kalaulah perlu bicara politik di masjid, lebih baik bicara saja soal gagasan yang kreatif, inovatif, dan progresif. Katanya umat Islam sudah cerdas, maka jadikan masjid sebagai arena dialektika yang, dalam bahasa Muhammadiyah, mencerahkan dan berkemajuan.
Umat Islam harus berorientasi ke depan, jangan melulu meromantisasi kejayaan Dunia Islam abad pertengahan. Bolehlah menjadikan kejayaan Dunia Islam sebagai inspirasi, namun tentu kita harus berusaha supaya Dunia Islam hari ini lebih transformatif dan progresif daripada abad pertengahan.
Dengan begitu, Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin benar-benar mewujud ke dalam tindakan yang nyata secara kolektif, bukan hanya konsep yang mengambang di pikiran individu.