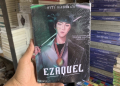Pekalongan – Beragam etnis yang mendiami wilayah Pekalongan, menjadi warna tersendiri dalam tumbuh kembang kota di Pesisir Utara Pulau Jawa ini. Salah satunya etnis Tionghoa yang sudah sejak lama berhubungan dengan penduduk pulau Jawa.
Saat ekspedisi pelayaran Panglima Cheng-Hoo beberapa kali singgah ke Jawa. Kemudian sekretarisnya bernama Ma-Huan sempat masuk pedalaman sungai Pekalongan. Kehadiran orang-orang dari daratan Tiongkok ini memang membawa berbagai pengaruh perubahan kultur dan budaya di tanah Jawa. Mereka memiliki kemampuan dalam mengolah hasil alam untuk menjadi komoditas perdagangan yang menguntungkan.
Bahkan jauh sebelum VOC menginjakan kakinya di Sunda Kelapa, tepatnya saat Demak dan Cirebon menguasai wilayah Pekalongan. Tidak mengheran jika etnis Tionghoa sudah dipercaya untuk mengelola Pelabuhan Pekalongan. Kondisi ini semakin dikuatkan sejak awal Mataram Islam berkuasa di tanah Jawa, beberapa orang Tionghoa dipercaya untuk menjadi bupati.
Baca juga : Kisah KH. Abdul Gaffar Ismail di Pekalongan
Pada era Sultan Agung, seorang etnis Tionghoa bernama Cik Go Ing dipercaya menjadi Bupati Lasem. Cik Go Ing diangkat menjadi bupati karena jasanya membantu Mataram berperang melawan Surabaya. Semenjak itulah raja-raja Mataram mulai mempercayakan bupati-bupati wilayah pesisir pada orang Tionghoa peranakan. Amangkurat III sebagai penguasa Mataram kemudian mempercayakan kekuasaan Pekalongan pada Klan Djayadiningrat keturunan Tionghoa (sering disebut sebagai Tan Kwee Djan).
Sosok Adipati Djayadiningrat (Tan Kwee Djan) sangat menarik untuk dibahas, karena beliau ini sukses menjadi Bupati dan sekaligus menjadi Pengusaha yang banyak menginvestasikan uangnnya di berbagai sektor.
Baca juga : Sejarah Asal-Usul Nama Desa Kwijan Pekalongan
Amangkurat III pada tahun 1703 secara resmi mengangkat Tan Kwee Djan sebagai Bupati Pekalongan dan sebagai kepala tituler pesisir Kilen dengan gelar Tumenggung. Djayaningrat atau Djayadiningrat merupakan anak pemungut pajak asal Makasar yang dipercaya Mataram untuk menarik pajak di wilayah Salatiga. Bapaknya Djayadiningrat juga seorang pedagang yang menguasai jalur Semarang-Kartasura.
Untuk menguatkan posisi Djayaningrat dalam menjalin hubungannya dengan Mataram di Pesisir Barat, maka anaknya bernama Tumenggung Suradiningrat dinikahkan dengan putri Patih Danurejo. Sedangkan putra pertama Djayadiningrat yaitu Jayanegara menjabat sebagai Bupati Lembahrawa.
Dalam setiap tahunnya Bupati Djayaningrat diminta untuk wajib hadir dalam perayaan Maulid yang digelar keraton Mataram dan wajib menyerahkan hadiah langsung pada Raja Mataram. Djayadiningrat dikenal sangat piawai menjalankan kerajaan bisnisnya ditambah kepercayaan sebagai Kepala Pesisir Barat.
Dia memperoleh pendapatan dari pajak dan memperoleh keuntungan besar dari menjual beras, merica,dan gula pada VOC. Djayadiningrat pun dipercaya oleh VOC sebagai bupati pesisir pertama yang memulai budiaya pewarna Nila atau Indigo serta kopi.
Baca juga : Mengenal Eliza Van Zuylen Maestro Seniman Batik Indo-Eropa
Djayadiningrat oleh VOC ditawari kerjasama untuk melakukan investasi budidaya indigo. Djayadiningrat memilih dua lokasi untuk mulai menaman indigo yaitu di Ambarawa dan Pekalongan.
Produksi tanamana untuk pewarna kain ini di mulai sejak tahun 1709 dengan tambahan lokasi penanaman di Batang, Wiradesa, Pemalang, dan Kaliwunggu. Keuntungan yang cukup besar dari indigo ini membuat iri bupati lain diantaranya: Bupati Kudus, Jepara,dan Pati.
Akhirnya para bupati itu juga ikut mulai terlibat investasi. Proses pengolahan tanaman indigo membutuhkan modal yang besar dan keahlian dalam mengolahnya.
Sementara untuk Kopi, Gubernur Joan Van Hoorn pada tahun 1709 mulai membudidayakan kopi dengan mengirim 10 peti berisi bibit kopi untuk ditanam di wilayah Semarang. Namun, budidaya ini mengalami kegagalan karena Bupati Semarang tidak mengerti tentang tata cara penanaman kopi. Kondisi pertanian di daerah pesisir Pantai Semarang ternyata tidak cocok untuk tanaman kopi.
Baca juga : Mengenal Jenderal Hoegeng Imam Santoso
Mendengar cerita ini, Bupati Pekalongan Djayadininrat yang memiliki jiwa wirausaha rupanya tertarik untuk membangun investasi dari perkebunan kopi yang dinilai akan memberi keuntungan besar. Pada 1715 Djayadiningrat I mulai menanam sebanyak 4 ribu bibit kopi.
Ternyata 500 biji diantaranya tumbuh dengan hasil yang cukup baik di Pekalongan bagian Selatan. Padalah sebelumnya para petinggi VOC di Batavia sempat merasa pesisimis. Dalam waktu 3 tahun, Djayadiningrat melaporkan pada VOC, bahwa Ia telah memiliki 30 ribu tenaman kopinya dengan pertumbuhan sangat baik.
Lalu pada tahun 1719 tanaman kopi milik Jayadiningrat telah mencapai 40 ribu pohon. Dengan demikian tanaman kopi Pekalongan meningkat secara proporsional.
Bupati Djayaningrat banyak menginvestasikan uangnya karena memiliki kekuasaan sehingga bisa mengendalikan kekuasaan di wilayahnya. Bagian keuntungan dari kerajaan bisnisnya diinvestasikan kembali sehingga keuntungannya bisa berlipat-lipat dan hasilnya juga meningkatkan posisinya secara politik di kerajaan Mataram.
Baca juga : Kisah Pak Dhe Dele, Sang Penjahit Jenius Dari Pekalongan
Djayaningrat sebenarnya berasal dari Makasar. Ketika tiba di wilayah Pekalongan dan menjadi bupati, ia merekrut banyak tentara bayaran yang berasal dari Makasar maupun dari daerah bukan Jawa. Ia mempersenjatai seluruh pengikutnya dengan senjata tombak ketika terjadi pembrontakan di Tegal Adipati yang telah berkuasa selama 23 tahun ini kemudian meninggal tanggal 12 Desember 1726 dan digantikan oleh anaknya Tumenggung Suradiningrat dengan gelar Djayadningrat II.

Raja Mataram Susuhunan Paku Buwono ke II mengangkat Suradiningrat sebagai penganti ayahnya pada bulan November 1733.Djayaningrat kemudian meneruskan kerajaan bisnis milik ayahnya. Ia mengalami kegagalan karena harga indigo dan kopi di pasaran Eropa anjlok.
Setelah berkuasa selama 10 tahun Djayaningrat II meninggal pada bulan 11 Juli 1743 di Ampel ketika dalam perjalanan menuju ke Kartasura untuk menghadiri perayaan Maulud.
Jayaningrat III lalu digantikan oleh menantunya Sumadiwirya, yang juga putra dari Patih Natakusuma. Sebelumnya dia mendapat gelar Raden Arya Sumadiningrat. Setelah menjadi Bupati Pekalongan, gelarnya berganti menjadi Raden Adipati Jayaningrat 3. Ia meninggal sekitar tahun 1743 dan digantikan Djayaningrat IV yang berkuasa hingga tahun 1790.
Baca juga : Sejarah Gedung Pendopo Pekalongan
Residen Rothenbuhler ketika berkunjung ke Pekalongan tahun 1789 pernah menemui Jayadiningrat IV. Ia bercerita bahwa kakek dari Jayadiningrat IV adalah seorang Tionghoa yang telah memeluk agama Islam. Klan Adipati Djayaningrat berkuasa di Pekalongan hingga 4 periode. Klan ini berakhir tahun 1790 ketika VOC sudah mulai menancapkan kekuasaanya di pesisir Pekalongan setelah perjanjian Giyanti.
(Ensiklopedia Tokoh Pekalongan – Dirhamsyah, 2011)